ISLAM DAN NEGARA
Dalam Wacana Pemikian Islam
A. Pengantar
Wacana pemikiran Islam tentang hubungan agama dengan negara mengalami sebuah dinamisasi terutama pasca kebangkrutan pemerintahan khilafah Islam terakhir, Turki Usmani. Hal ini disebabkab oleh beberapa faktor. Pertama, terjadinya pergeseran paradigma pemikiran agama yang dimulai sejak ekspansi Prancis atas Mesir yang menyebabkan hentakan psikologi ummat Islam akan fakta kemajuan bangsa-bangsa di luar Islam. Keadaan ini meyadarkan ummat Islam, semisal Jamaluddin Afgani, Muhammad Abduh dan lain-lain, untuk segera melakukan upaya pembaruan sikap yang tentunya harus dimulai dari pembaruan paradigma. Sejak itu pergeseran paradigma mulai terjadi dalam benak ummat Islam dan menjadi usaha yang nampak niscaya untuk menggapai kemajuan. Kedua, akibat perkembangan modernisasi yang melanda dunia, termasuk di dalamnya dunia Islam yang secara berangsur-angsur menempatkan modernisasi dengan implikasinya sebagai keharusan sejarah. Akibatnya, terjadi pergeseran singnifikan terhadap tafsir bentuk negara ideal yang menyeret debat seputar bagaimana peran agama dalam menentukan pemerintahan dalam sebuah negara modern yang majemuk. Terutama sekali seperti apa yang terjadi pada negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam, seperti Indonesia, Sudan, Turki, Malaysia dan lain-lain.
Pada perkembangan selanjutnya, semangat pembaruan pemikiran tersebut, khususnya wacana agama dengan negara, mengalami dinamisasi internal. Hingga muncul adanya pemikiran pentingnya dilakukan rekonstruksi pemahaman atas tafsir keagamaan ummat Islam, termasuk di dalamnya debat seputar interrelasi agama dengan negara yang menjadi salah satu pokok penting dalam pemikiran politik Islam, baik dalam bentuknya yang normatif maupun historis.
B. Pembahasan
Dari pokok pikiran yang berkembang dalam diskursus pemikiran politik Islam, masing-masing kelompok tersebut dapat digolongkan dalam tiga tipologi. Pertama, kelompok yang menempatkan agama sebagai subordinasi atas negara dan memandang interrelasi agama dengan negara sebagai keharusan integralistik. Kelompok ini memandang agama sebagai institusi yang sempurna dalam mengontrol kehidupan sosial-politik manusia, sehingga pendekatan lain tidak diperlukan lagi. Model ini dapat dijumpai jejaknya pada tokoh-tokoh pemikir Islam, semisal Almaududi, Ali Jinnah, Natsir.
Kedua, kelompok yang melihat kemungkinan adanya negoisasi terhadap aspek-aspek dari luar sepanjang tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip universalisme agama Islam. Kelompok ini toleransif dan melihat celah dilakukannya jastifikasi terhadap anasir luar, semisal demokrasi, HAM dan isu lainnya yang bisa saja dipertimbangkan.
Ketiga, kelompok yang memandang interrelasi agama dengan negara berada dalam ruang yang terpisah atau sekuler. Dalam pandangan komunitas ini, agama tidak boleh dijadikan jastifikasi atas kehidupan politik suatu bangsa. Tentu saja argumen yang dikemukakan oleh kelompok terakhir ini mempunyai segmen bahasan yang cukup kuat tentang bagaimana seharusnya sekularisme, hubungannya dengan universalisme agama atau pesan-pesan normatif agama Islam yang tertuang dalam cakupan nash (Alquran dan Sunnah).
Berdasarkan tiga tipologi di atas, wacana interrelasi agama dengan negara menjadi ide terapan pada masing-masing pemikirnya. Usaha menurunkan pemikiran tentang agama dengan negara dalan tingkatan praktik dapat dilihat pada beberapa usaha-usaha para penggiatnya, misalnya seruan Maududi terhadap negara Islam Pakistan yang hingga hari ini tetap relevan terjadi. Atau apa yang terjadi pada negara Turki oleh Mustafa Kemal dengan kemalismenya yang mempraktekkan Turki sekuler. Di Indonesia hingga hari ini, konteks negara agama tetap saja ramai dipelopori dengan variabel yang beragam, dari yang ilegal hingga dianggap konsitusional.
1. Tipologi Integralistik
Tipologi ini melihat bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (din wa daulah). Ia merupakan agama yang sempurna dan antara Islam dan negara merupakan dua entitas yang menyatu. Hubungan Islam dan negara benar-benar organik dimana negara berdasarkan syari’ah Islam dengan ulama sebagai penasehat resmi eksekutif atau bahkan pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai agama sempurna, bagi pemikir politik Islam yang memiliki tipologi seperti ini, Islam bukan sekedar agama dalam pengertian Barat yang sekuler, tetapi merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk politik.[1] Rasyid Ridha, Sayyid Qutub dan Abu al-‘ala al-Maududi.
1. Rasyid Ridha
Rasyid Ridha, sebagai seorang yang berkecenderungan tradisional begitu percaya dengan lembaga kesultanan Usmani yang menurutnya adalah juga kekhalifahan, walaupun mereka bukan dari keturunan Quraisy dan Arab. Ia tampaknya menutup mata terhadap despotisme kesultanan Usmani. Kekhalifahan Usmani baginya merupakan pranata politik supra nasional yang mewakili nabi pasca Abbasiyah yang mempersatukan umat Islam di berbagai belahan dunia yang perlu dihidupkan dengan tugas untuk mengatur urusan dunia dan agama, suatu pemikiran yang sama persis dengan pemikiran al-Mawardi. Alasannya karena Al-Qur’an, hadis dan ijma’ pun menghendakinya.[2]
Tentu saja ahl al-hall wa al-‘aqd, sebagai lembaga pemilih khalifah juga perlu dibentuk. Hanya saja ia lebih maju dibanding pemikir politik Islam klasik yang realis pada masa klasik dan pertengahan, walaupun untuk khalifah menurutnya mesti seorang ahli fiqh yang karenanya untuk mempersiapkannya perlu didirikan lembaga pendidikan tinggi keagamaan, tetapi untuk ahl al-hall wa al-‘aqd anggotanya bukan saja ahli agama yang sudah mencapai tingkat mujtahid melainkan juga pemuka masyarakat dari berbagai bidang.
Selain itu, berbeda dengan pemikir politik sebelumnya, lembaga representatif itu dalam pandangannya juga bertugas mengangkat khalifah, mengawasi jalannya pemerintahan, mencegah penyelewengan khalifah dan perlu menurunkannya jika perlu, sekalipun harus dengan perang atau kekerasan demi kepentingan umum. Meskipun pandangan-pandangan Rasyid Ridha sulit diterima untuk konteks kekinian, di mana Rosenthal menganggapnya berada dalam posisi utopis dan romantis,[3] bagaimanapun Rasyid Ridha telah berhasil memformulasikan tradisi dan merancangkan gagasan dasar bagi para penganjur negara Islam berikutnya.
Ia merupakan penghubung yang penting antara teori klasik tentang kekhalifahan dengan gagasan mengenai negara Islam pada abad ke-20 yang dikembangkan oleh Sayyid Quthb dan al-Maududi. Keduanya telah mengembangkan yang dalam istilah Profesor Majid Khadduri, devine nomocracy (negara hukum Ilahi) atau menurut Istilah Profeser Tahir Azhari Nomokrasi Islam.[4]
2. Sayyid Qutub dan al-Maududi
Seperti halnya Rasyid Ridha, Sayyid Quthb menginginkan bentuk pemerintahan supra nasional (kesatuan seluruh dunia Islam) yang sentralistis, tetapi daerah tidak sebagai jajahan, mempersamakan pemeluk agama, dan didirikan atas tiga prinsip: keadilan penguasa, ketaatan rakyat karena hasil pilihannya dan permusyawarahan antara penguasa dan rakyat. Meskipun ia tidak mempersoalkan sistem pemerintahan apapun sesuai dengan sistem kondisi masyarakat, namun pemerintahan ini bercirikan penghormatan pada superemasi hukum Islam (syari’ah). Sayyid Quthb dan juga al-Maududi adalah orang pertama yang menggunakan pengertian bahwa umat manusia adalah khalifah Allah di muka bumi sebagai dasar teori kenegaraan. Keduanya menolak prinsip kedaulatan rakyat dalam pengertian konsep politik Barat, karena manusia hanyalah pelaksana kedaulatan dan hukum Tuhan yang sebab itu, manusia tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Konsep politik Islam ini oleh al-Maududi disebut sebagai Theo-Demokrasi.
Istilah Theo-Demokrasi berasal dari dua kata, theokrsasi dan demokrasi. Dua kata yang disatukan dalam istilah ini dijelaskan Maududi bahwa kewenangan untuk menegakkan pemerintahan yang diberikan Tuhan kepada manusia dibatasi oleh undang-undang Nya yakni syari’at.[5] Manusia diberik kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat yang melanggar atura Tuhan. Hal-hal yang tidak jelas diatur secara jelas dalam syari’at diselesaikan berdasarkan musyawarah dan konsensus kaum muslimin. Mukmin yang memiliki persyaratan dan kemampuan berijtihad diberi kesempatan untuk menafisrkan undang-undang Tuhan jika diperlukan. Undang-undang yang sudah jelas terdapat dalam nash tidak boleh seorang pun mengubah atau membantahnya. Penafsiran terhadap undang-undang yang belum jelas pengertiannya tidak boleh kontradiktif dengan ketentuan umum undang-undang Tuhan.
Pemikiran pembaruan politik al-Maududi tentang teori politik pemerintahan didasari oleh tiga prinsip. Menurutnya, sistem politik Islam didasari oleh tiga prinsip tersebut, yaitu Unity of God (tauhid), Prophethood (risalah) dan Caliphate (khilafah). Aspek politik Islam akan sulit dipahami tanpa memahami secara keseluruhan akan ketiga prinsip ini.
Tauhid berarti hanya Tuhan sendirilah pencipta, penguasa dan pemelihara. Karena Tuhan adalah penguasa, segala kedaulatan di alam ini berada pada Tuhan. Dengan demikian, segala perintah dan laranganNya adalah undang-undang sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim bahwa dirinya memiliki kedaulatan.
Risalah menurut Maududi adalah bahwa undang-undang dari Tuhan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Perbuatan Rasulullah dengan melakukan interpretasi terhadap undang-undang itu melalui perkataan dan perbuatannya disebut sunah. Inilah yang disebut sebagai Risalah Muhammad, yang berisi segala norma dan pola hidup bagi manusia yang disebut syari’ah.
Khilafah, ia jelaskan dengan ungkapannya bahwa manusia di muka bumi ini diberi kedudukan sebagai Khalifah (perwakilan), yang berarti bahwa manusia adalah wakil Tuhan di bumi. Manusia yang dimaksudkannya adalah seluruh komunitas yang meyakini dan menerima prinsip-prinsip bahwa pemegang kepemimpinan dan yang berkuasa di alam ini adalah Tuhan, kedaulatan tertinggi ada pada Tuhan. Dengan demikian, setiap manusia yang menerima prinsip ini berarti telah menduduki posisi khilafah. Akan tetapi, manusia yang diserahi khilafah yang sah dan benar ini bukanlah perorangan, keluarga atau kelas tertentu, melainkan komunitas yang meyakini dan menerima prinsip-prinsip yang telah disebutkan dan bersedia menegakkan kekuasaannya atas dasar prinsip tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan khilafah itu haruslah kolektif, dan Maududi menyebut teori khilafahnya yang demikian dengan nama khilafah kolektif.
Untuk memperjelas mekanisme khilafah dalam rangka melaksanakan kedaulatan Tuhan, Maududi memberikan ilustrasi sebuah perusahaan yang pengelolaannya diserahkan pada orang yang bukan pemiliknya. Perusahaan yang demikian haus memberlakukan empat syarat. Pertama, pemilik sebenarnya bukanlah si pengelola. Kedua, pengelola harus mengelola perusahaannya dengan instruksi-instruksi pemilikinya. Ketiga, pengelola harus melaksanakan kekuasaannya dalam batas-batas yang telah ditentukan pemiliknya. Keempat, pengelola itu harus melaksanakan administrasi perusahaan itu berdasarkan kehendak pemiliknya, bukan atas kehendaknya sendiri.[6]
B. Tipologi Sekuler
Kebalikan dari tipoligi pertama, menurut tipologi ini Islam adalah agama yang tidak berbeda dengan agama lainnya dalam hal tidak mengajarkan cara-cara pengaturan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam adalah agama murni bukan negara. Pemikir yang masuk dalam tipologi ini adalah Ali Abd al-Raziq dan Luthfi al-Sayyid.
Pada bulan Maret 1924, Kemal Attaruk, Kepala Negara Turki mengumumkan dihapuskannya jabatan khilafah dari negaranya Dia mengklaim lembaga khalifah terbukti tidak bisa berfungsi sejak awal. Setelah kejadian penghapusan khalifah ini, tepatnya April 1925, Syekh Ali Abd al-Raziq, seorang hakim Syar’iyyah di al-Manshurah menerbitkan sebuah buku kontroversial yang menuntut dihapuskannya kekhilafahan dan mengingkari eksistensinya dalam ajaran Islam. Penerbitan buku ini mendapatkan reaksi yang luar biasa dari kalangan umat Islam di seluruh dunia. [7] Judul buku tersebut adalah al-Islam wa Ushul al-Hukm.
Tesis utama dari buku ini adalah:[8]
1. Nabi Muhammad tidak membangun negara dan otoritasnya murni bersifat spritual.
2. Bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif. Karena umat Islam boleh memilih bentuk pemerintahan apa pun yang dirasa cocok.
3. Bahwa tipe-tipe pemerintahan yang dibentuk setelah wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Sistem ini semata-mata diadopsi oleh orang-orang Arab dan dinaikkan derajatnya dengan istilah khilafah untuk memberi legitimasi religius.
4. Bahwa sistem ini telah menjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam karena ia digunakan untk meligitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam.
Dalam sistematikanya, buku tersebut terbagi menjadi tiga bagian.[9]
1. Dalam bagian pertama diuraikan tentang definisi khilafah atau lembaga khalifah beserta ciri-ciri khususnya, kemudian dipertanyakan tentang dasar anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan pola khilafah itu merupakan suatu keharusan dalam agama Islam, dan akhirnya dikemukakan bahwa baik dari segi agama maupun dari segi rasio, sistem pemerintahan khilafah itu tidak perlu.
2. Dalam bagia kedua diuraikan tentang pemerintahan dan Islam, tentang perbedaan antara risalah atau misi kenabian dengan pemerintahan, dan akhirnya disimpulkan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama bukan negara.
3. Dalam bagian ketiga dan terakhir diuraikan tentang khilafah atau lembaga khilafah dan pemerintahan dalam sejarah. Dalam hal ini Abd al-Raziq berusaha membedakan antara mana yang Islam dan mana yang arab, mana yang khilafah Islamiyah dan mana yang negara Arab, serta mana yang agama dan mana yang politik.
Masalah yang paling mendasar dalam karya Abd al-Raziq sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Diya al-Din Al-Rayis[10] adalah pandangannya bahwa Islam tidak punya sangkut paut dengan masalah kekhalifahan. Menurutnya kekhalifahan, termasuk yang berada di bawah kekuasaan al-khulafa’u al-Rasyidun bukanlah sistem Islam ataupun keagamaan, tapi sistem yang pada dasarnya duniawi.
Argumen pokok Ali ‘Abd al-Raziq adalah bahwa kekhalifahan tidak ada dasarnya baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Keduanya tidak menyebut kekhalifahan dalam pengertian seperti yang terjelma dalam sejarah. Lebih lanjut, tidak ada penunjukkan yang jelas baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah mengenai bentuk sistem politik yang harus dibangun umat Islam.
Ali Abd al-Raziq bahkan lebih lanjut berargumen bahwa kata-kata seperti uli al-amr (mereka yang berkuasa) dalam al-Qur’an (QS 4: 26) yang diklaim oleh banyak pemikir sebagai kekhalifahan atau imamah, tidak ada sangkut pautnya dengan institusi ini dan tidak dimaksudkan untuk mendirikan kekuasaan kekhalifahan. Dengan mengacu pada mufassir besar al-Qur’an seperti Baidhawi dan Zamakhsyari, ia katakan bahwa kata-kata itu ditafsirkan sebagai sahabat Nabi atau ulama. Ia juga membantah bahwa Nabi Muhammad telah membentuk negara Islam di Madinah nabi hanyalah Rasulullah, bukan raja atau pun pemimpin politik.[11]
Di sinilah Ali Abd al-Raziq bermaksud membedakan antara agama dan politik, atau lebih tepatnya antara misi kenabian dan tindakan politik. Ia memberikan argumen historis dan teologis cukup panjang dalam buku tersebut untuk menunjukkan bahwa tindakan politik Nabi, misalnya melakukan perang, memungut pajak dan zakat dan bahkan jihad, tidak berkaitan atau tidak mencerminkan fungsi Nabi sebagai utusan Allah. Baginya, Islam adalah entitas keagamaan yang bertujuan membangun kesatuan masyarakat yang diikat oleh keyakinan bersama, melalui dakwah agama.
Dalam bukunya tersebut tersirat bahwa Ali Abd al-Raziq tidak bermaksud mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak perlu membentuk pemerintahan. Sebaliknya, Islam tidak menolak perlunya suatu kekuasaan politik. Dalam al-Qur’an, menurutnya Tuhan menyatakan perlunya pembentukan suatu pemerintahan sebagai sarana esensial bagi umat Islam dalam perjuangan mereka untuk melindungi agama dan menyalurkan kepentingan-kepentingannya. Tapi ini tidak berarti bahwa pembentukan suatu pemerintahan menjadi ajaran pokok Islam. Ini jelas menunjukkan bahwa Ali menerima keberadaan otoritas politik dalam umat Islam. Tapi ia jelas menolak bahwa otoritas politik merupakan tuntutan syariah atau bentuk organisasi politik yang wajib ada secara keagamaan. Bahkan bagi Ali Abd al-Raziq pemerintahan kekhalifahan Islam merupakan fenomena historis murni yang pada dasarnya bersifat sekuler.
Orang lain yang memiliki persamaan pendapat dengan Ali Abd al-Raziq adalah Ahmad Luthfi al-Sayyid.[12] Menurutnya agama dan negara adalah dua hal yang berbeda. Dalam membangun negara, kaumMuslimin tidak harus mengikatkan diri pada Islam dan pan Islamisme karenanya tidak lagi relevan.
Program Ahmad Luthfi al-Sayyid adalah memadukan antara prinsip-prinsip Islam dan filsafat Yunani, gagasan-gagasan pencerahan Prancis dan liberalisme Inggris. Pemaduan pemikiran ini membawa Ahmad Luthfi al-Sayyid memusatkan perhatiannya pada sejumlah prinsip yang dapat mempertegas garis-garis pokok pemikiran yang ia tampilkan dan yang secara keseluruhannya terwujud dalam liberalisme Mesir pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad ke-20. Prinsip-prinsip tersebut adalah mendirikan suatu pemerintahan bercorak sekuler yang didasarkan atas asas manfaat, menafsirkan agama hanya dalam kerangka hubungan manusia dan Tuhannya, menentukan kriteria-kriteria perilaku perorangan dan akhirnya mempertegas gagasan nasionalisme Mesir.
Perlu juga disebutkan bahwa ketika Partai Umat dibentuk, dengan penamaan umat di situ tidak dimaksudkan umat dalam konsepsi Islam melainkan umat bangsa Mesir yang terdiri dari orang-orang Kristen, Yahudi dan Islam yang semuanya tidak disatukan oleh hukum syari’at, melainkan oleh hubungan-hubungan alamiah yang lahir dari kehidupan bersama di tempat yang sama. Lebih lanjut, seperti ditegaskan oleh Ahmad Luthfi al-Sayyid, Islam bukanlah dasar Nasionalisme.
C. Tipologi Pemikiran Politik Islam Moderat
Berbeda dengan dua kecenderungan tipologi di atas adalah tipologi ketiga yang moderat. Tipologi ini menolak klaim ekstrim bahwa Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua urusan termasuk politik, tetapi juga menolak klaim ekstrim kedua yang melihat bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan politik. Menurut tipologi ini, kendati Islam tidak menunjukkan preferensinya pada sistem politik tertentu, tetapi dalam Islam terdapat prinsip-prinsip moral atau etika bagi kehidupan bernegara, yang untuk pelaksanaannya Umat Islam bebas memilih sistem mana pun yang terbaik. Yang termasuk tipologi ini adalah Muhamad Husein Haikal (lahir 1888), Muhammad Abduh (1862-1905), dan Fazlurrahman.
1. Muhamad Husein Haikal (lahir 1888)
Menurut Haikal, di dalam Al-Qur’an dan sunnah tidak terdapat prinsip-prinsip dasar kehidupan yang langsung berhubungan dengan ketatanegaraan. Ayat tentang musyawarah misalnya tidaklah diturunkan dalam kaitan sistem pemerintahan. Al Qur’an juga tidak secara tegas dan langsung menyebutkan sistem pemerintahan tertentu. Karenanya, tidak aneh bila empat khalifah periode Islam awal (Khulafa Rasyidun) memang di bai’at masyarakat di mesjid, tetapi mereka diangkat tidak selalu melalui pemilihan. Nabi sendiri bahkan membiarkan sistem pemerintahan Arab asalkan menerima baik agama yang dibawanya. Dalam perkembangan selanjutnya juga pengaruh luar (Bizantium dan Persia) terhadap pemerintahan Islam makin mendalam dan tampak.[13]
Namun demikian, sejauh yang bisa kita baca dari sumber-sumber Islam, paling tidak ada 3 prinsip dasar peradaban manusia termasuk politik. Pertama, prinsip monotheisme murni. Kedua, prinsip sunnah (hukum ) Allah yang tidak pernah berubah, dan ketiga, persamaan antar manusia sebagai konsekuensi prinsip pertama dan kedua. Realisasi prinsip-prinsip itu diwarnai oleh semangat persaudaraan, cinta kasih, rasa keadilan, dan takwa.
2. Muhammad Abduh (1862-1905)[14]
Muhammad Abduh, meskipun hidup jauh sebelum Haikal dan guru dari Ridha mauppun Raziq, tampaknya masuk kategori ketiga. Dalam pandangan Abduh, Islam tidak menetapkan suatu bentukpemerintahan. Jika bentuk khilafah masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan maka bentuk demikian pun harus mengikuti perkembangan masyarakat. Ini me-ngandung makna bahwa apa pun bentuk pemerintahan, Abduh menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis. Dengan demikian, ia mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Pendapat demikian adalah konsekuensi dari konsep teologisnya tentang kehendak bebas manusia sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Tentang sumber kekuasaan, Abduh menegaskan rakyat adalah sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyatlah yang mengangkat dan yang mempunyai hak memaksa pemerintah. Karenanya rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan mereka. Karena sumber kekuasaan adalah rakyat, Islam tidak mengenal kekuasaan agama seperti yang terdapat dalam Kristen Katolik pada abad pertengahan di Barat. Islam tidak memberi kekuasaan kepada seorang pun selain kepada Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak menghendaki seseorang mempunyai kekuasaan terhadap akidah dan keimanan orang lain. Bahkan seorang mufti, qadhi atau syaikhul Islam tidak memiliki kekuasaan agama. Islam hanya mengenal satu kekuasaan, yaitu kekuasaan politik. Kekuasaan politik itu berhubungan dengan urusan keduniaan yang tidak berlandaskan agama.
Jelasnya menurut Abduh, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama dalam arti: (1) Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau berdasarkan mandat agama atau dari Tuhan; (2) Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, penguasa sekalipun, dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain; (3) Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat, dan penafsirannya tentang agama atas orang lain.[15]
Bahkan, menurut Abduh, salah satu prinsip dari ajaran Islam adalah mengikis habis kekuasaan keagamaan sehingga setelah Allah dan Rasulnya, tidak akan ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan atas akidah dan iman orang lain. Bukankah Nabi Muhammad hanyalah seorang mubalig dan pemberi peringatan tanpa hak untuk memaksakan ajarannya. Tidak ada seorang muslim, bagaimanapun tinggi keduduk-annya, yang mempunyai hak untuk memberikan nasihat dan penyuluhan. Dalam Islam juga tidak terdapat penguasa agama yang atas nama agama, atau berlandaskan mandat dari langit, dapat mengangkat dan menurunkan raja, memungut pajak dan upeti, serta mengundangkan hukum ilahi, seperti yang pernah terjadi dalam sejarah sementara agama.
Pendapat Abduh di atas seperti mengisyaratkan ketidak-sepakatan pendapatnya dengan sementara pemikir politik Islam zaman klasik dan pertengahan yang menyatakan bahwa kekuasaan raja atau khalifah itu merupakan mandat dari Allah, dan karenanya ia bertanggung jawab kepada Allah pula. Menurut Abduh, seorang khalifah atau kepala negara adalah seorang penguasa sipil yang pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak manusia atau rakyat dan bukan hak Tuhan.
Abduh mengakui bahwa bahwa Islam itu bukan agama semata-mata, melainkan mempunyai hukum-hukum yang mengatur hubungan antarsesama muslim dan sesama hidup, yang untuk pelaksanaan dan pengawasan berlakunya memerlu-kan adanya penguasa lengkap dengan aparatny/a. Menurutnya, tugas itu merupakan tanggung jawab kepala negara beserta perangkat pemerintahnya. Tetapi kepala negara sebagai penguasa sipil diangkat oleh rakyat dan bertanggung jawab kepadanya. Rakyat adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya dan berhak menurunkan kepala negara dari takhta. Kepala negara bukanlah wakil atau bayangan Tuhan di bumi, yang mewajibkan tiap muslim taat kepadanya demi agama meskipun perilaku dan kebijaksanaannya bertolak belakang dengan ajaran agama. Lebih jauh Abduh menyatakan bahwa kalau khalifah atau raja saja tidak memiliki kekuasaan keagamaan, lembaga-lembaga pemerintahan di bawah kepala negara lebih tidak mempunyai kekuasaan agama, termasuk lembaga fatwa dan jabatan syaikhul Islam atau mufti. Mereka dapat saja memberikan opini hukum atau fatwa, tetapi tidak dapat dipaksakan.
Dalam hal ketaatan, rakyat tidak boleh menaati pemimpin yang berbuat maksiat. Apabila pemimpin melakukan hal yang bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah, rakyat harus meng-gantinya dengan orang lain, selama dalam proses penggantian itu tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada maslahat yang ingin dicapai.
Dengan kekuasaan politik, Abduh menghendaki agar prinsip-prinsip ajaran Islam dapat dijalankan oleh yang mempunyai hak dan wewenang pemerintah. Tapi Islam tidak memberi peluang akan munculnya sistem teokrasi. Usaha pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Undang-undang yang adil dan bebas bukanlah didasarkan pada prinsip-prinsip budaya dan politik negara lain. Kata Abduh, harus ada hubungan yang erat antara undang-undang dan kondisi negara setempat.
Dari pendapat-pendapatnya tampaknya Abduh berpendirian bahwa pemerintahan itu tidak berdasarkan agama, tetapi memiliki tugas keagamaan untuk memelihara nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang umum. Persepsinya tentang negara dan pemerintahan, lanjut Sayuti, mencerminkan bahwa ia tidak meng-hendaki pemerintahan eksklusif untuk umat Islam; ia juga dapat menerima negara kesatuan nasional yang berkembang di zaman modern. Pikiran-pikiran keagamaannya pun bersifat antisipatif terhadap perubahan zaman. Yang lebih penting, ia tetap mem-punyai komitmen yang tinggi terhadap Islam. Karena baginya kekuasaan politik yang ada di samping mengurus dunia, juga harus melaksanakan prinsip-prinsip Islam.
3. Fazlurrahman
Bila Haikal tidak menyebut preferensi Islam pada sistem politik tertentu, maka pemikir Islam setelahnya, yaitu Fazlur-Rahman, Mohamed Arkoun, dan di Indonesia Nurcholish Madjid, menyebut bahwa dari prinsip-prinsip yang disebut Al-Qur’an dan Hadis, preferensi Islam adalah sistem politik demokratis. Dalam berbagai tulisannya Fazlur-Rahman menekankan masyarakat Islam adalah masyarakat menengah yang tidak terjebak pada ekstrimitas, dan ûlil al-amri-nya (para pemegang kekuasaan) adalah mereka yang tidak menerima konsep elitisisme ekstrim. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang egaliter dan terbuka atau inklusif, saling berbuat baik dan kerjasama, dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan gender atau kulit.
Selanjutnya Fazlur Rahman[16] menjelaskan konsep syûra (musyawarah). Syûra bukan berarti bahwa seseorang meminta nasehat kepada orang lain, seperti yang terjadi dahulu antara khalifah dan ahl halli wa al–‘alqd, tetapi nasehat timbal balik melalui diskusi bersama. Tentu saja konsep demokrasi yang dipilih Fazlur Rahman ini dengan, katanya lebih lanjut, berorientasi pada etika dan nilai spiritual Islam, tidak semata-mata bersifat material seperti di Barat. Karena pilihannya pada sistem demokrasi itulah, ia mengkritik para tokoh Islam yang menentang demokrasi, seperti terhadap al- Maududi seperti yang telah dijelaskan di muka.
Sebagaimana Fazlur-Rahman, Arkoun juga berpendapat sama. Pertama-tama ia menjelaskan perbedaan antara kekuasan dan wewenang. Wewenang menurutnya bersifat mistis-teologis seperti ketika Nabi di Mekah dan kekuasan bersifat rasional seperti ketika Nabi di Madinah yang selalu dikelilingi dewan yang beranggotakan paling tidak 10 orang. Selanjutnya, Arkoun menerima pernyataan Ibn Khaldun bahwa sistem kekhalifahan tidak berbeda dengan sistem kerajaan yang dominatif dan hegemonik yang telah melakukan tindakan sakralisasi terhadap yang duniawi seperti terlihat pada terminologi bai’ah dan wakil Allah di muka bumi. Dari sini kemudian ia lebih menyetujui negara demokratis, mengkritik para ulama yang telah ikut melestarikan status quo kekuasaan dinasti yang jauh dari moral Islam, dan mengecam pelaksanaan konsep dzimmi (yang terlindung) bagi masyarakat non Muslim.
Dalam pandangannya, kendati penerapan konsep itu lebih baik dibanding dengan kaum Muslimin yang hidup di tengah mayoritas umat agama lain, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa model toleransi dzimmi tersebut adalah model toleransi tanpa peduli. Ini karena ia biasanya disertai dengan tindakan mengurangi peran kelompok lain yang non Muslim. Sebagai pemikir modern, Arkoun di satu sisi mengkritik habis
sekularisasi gaya Ataturk di Turki yang bagi Arkoun merupakan bentuk kesadaran naif yang didasari oleh kekagetan budaya, tetapi di pihak lain ia juga menolak pembentukan negara Islam, ala Khomeini karena telah melakukan sakralisasi terhadap sesuatu yang sebenarnya duniawi. Adapun prinsip kenegaraan dalam Islam adalah syûra, ijtihâd, dan penerapan syari’at yang tujuannya, bagi Arkoun, untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, bertanggung jawab, dan bermartabat, sehingga anggota masyarakat Muslim diridhai Allah dalam menjalankan tugas pribadi dan sosialnya secara harmonis.
[1] Ini biasa juga disebut dengan tipologi ideal totalistik. Tipologi ideal-totalistik diwakili oleh mayoritas pemikir keagamaan yang sangat committed kepada Islam sebagai doktrin seluruh aspek kehidupan. Kelompok ini percaya sepenuhnya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif untuk kebangkitan kembali sejarah kegemilangan kaum Muslim. Menurut kelompok ini, umat Islam harus kembali kepada ajaran asli Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Usaha penyucian Islam dari ajaran-ajaran asing baik yang berasal dari dalam (bid'ah kaum Muslim) maupun dari luar (Barat dan modernitas) menjadi agenda utama untuk mencapai keaslian ajaran Islam (Ashlah al-Islamiyah). Kemunduran yang dialami kaum Muslim sekarang ini disebabkan jauhnya mereka dari ajaran Islam. Usaha Islamisasi untuk segala aspek kehidupan Muslim menjadi agenda utama. Dari masalah etika, tingkah laku secara individu maupun sosial, hingga ilmu dan landasan epistemologi yang akan diserap oleh mereka, harus diislamkan, agar seluruh gerak dan tindakan yang hendak dilakukan oleh kaum Muslim adalah Islamis.
[2] Sebagaimana ulasan Bassam Tibi dalam the Challenge of Fundamentalisme yang diterjemahan dalam judul bahasa Indonesia, wacana Fundamentalisme; Islam Politik dan Dunia Baru, (Cet. I; Tiara Wacana; Yogyakarta, 2000). H. 63
[3] Dalam Gamal al-Banna, relasi Agama dan Negara, (Cet.I; Mata Air Publising: Jakarta, 2006), h. 32
[4] Ibid, h. 37
[5] Sebagaimana dikutip oleh Nurkhalis Madjid dalam Agama dan dialog antar peradaban, ed. Natsir Tamara, Cet. I; Paramadinah: Jakarta, 1996), H. 67
[6] Muhammad Sanusi, Pemikiran Politik Almaududi, skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin, 1994, h. 13
[7] Lihat, Nora Onar adalah peneliti pembantu pada Pusat Kajian Eropa, St. Antony's College, University of Oxford. Artikel ini disebarluaskan oleh Common Ground News Service (CGNews) dan dapat dibaca di www.commongroundnews.org
[8]Lihat, Syafiq al-Muqni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki, (Cet. I; Jakarta: logos, 1997), h . 123
[9] Lihat, Sherif Mardin, dalam Perkembangan Moderen Dalam Islam, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor), h. 246
[10] Sebagaimana dikutip kembali oleh Bassam Tibi, ibid, h. 87
[11] Loc.cit. al Mugni, h. 98
[12] Tentang Lutfi al-Syaukani dapat dilihat dalam artikel yang ditulis oleh Lutfi Asyaukani dalam blog bengkel Turast (Turats blogspot.com)
[13] Data ini diambil dari ensiklopedia Oxford, selengkapnya lihat The oxford Encylopedia of the Moden Islamic Wold, (vol. IV; New York: Oxfod University Press, 1995), h. 345-349
[14] Ibid, H. 340
[15] Nirwana, Pemikiran Muhammad Abduh, makalah disampaikan pada seminar kelas mata kuliah Pemikiran Islam Modern, konsentrasi Pemikiran Islam, 2008
[16] Tema-tema pembaharuan Fazlur Rahman tesebar dalam tulisan-tulisannya, baik jurnal, artikel maupun buku. Salah satunya lihat, Islamic Modernism; Its Scope, Method and Alternatives, (vol. IV; IJMES: Cambride), h. 321-335. lihat juga, Fazlurrahman, Islam dan Modernitas: Tentang Tronsformasi Intelektual, (Bandung; Pustaka Hidayah, 1995), h. 83
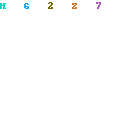

Post a Comment